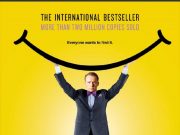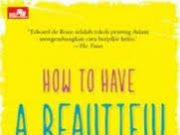Cerpen | DETaK
‘Manusia memang berubah-ubah, semoga dia tidak seperti yang sudah-sudah.’ Batinku yang selalu menguatkanku bahwa ada harapan untuk hubunganku dan dia. Meskipun di seberang sana aku tak dapat memantaunya secara leluasa.
“Jangan tidur terlalu malam, ya. Besok ada kuliah pagi kan?” ucapnya sebelum mematikan panggilan.
|
IKLAN
loading...
|
“Siap, komandan! Hehehe,” jawabku kegirangan.
Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11:00 malam, tapi tetap saja dua kelopak mata ini rasanya enggan sekali untuk dipejamkan. Kuraih kembali ponselku, kuputar lagu-lagu mellow untuk pengantar tidur sembari kubuka kembali album galeri yang berisikan kenangan dengannya. Kupandangi satu persatu momen yang pernah terabadikan dengannya.
‘Kamu sederhana dan aku mencintaimu.” Aku membatin sembari terus kupandangi potretnya. Sekarang aku berhenti pada satu potret ketika aku menghadiri acara pernikahan kakaknya. Ya, itu adalah potretku bersamanya di depan photo booth pernikahan kakaknya. Seketika ucapannya kembali terlintas di pikiranku. “Semoga nanti nama kita yang ada di sini,” ucapnya kala itu.
Aku hanya membalas perkataan itu dengan seutas senyuman dan pipi yang mulai merona. Ingin rasanya aku berteriak agar semesta tahu bahagianya aku ketika itu, namun aku tak kuasa melakukannya. Aku hanya bergeming di dalam hati, ‘Tuhan terima kasih telah hadirkan dia’.
Rasa kantuk perlahan menghampiri, kuputuskan untuk menutup kembali layar ponselku dan mulai beristirahat karena besok pagi ada mata kuliah Prosa Fiksi pukul 08:00 pagi.
“Zel… Zelline… Bangun sudah pagi.” Suara lelaki hebat itu terdengar di balik pintu kamarku.
“Iya, Yah. Kakak udah bangun kok,” jawabku sembari mengumpulkan arwah yang belum sepenuhnya pulang.
Sama seperti hari-hari lainnya, setiap pagi ayah tidak pernah absen membangunkanku. Meskipun sudah duduk di bangku kuliah, tetap saja bagi ayah aku adalah putri kecilnya. Satu persatu pekerjaan rumah telah selesai kukerjakan, tinggal waktunya menunggu dosen di depan laptop untuk memulai perkuliahan virtual. Sebenarnya aku tidak terlalu suka dengan sistem kuliah daring ini, namun apa boleh dikata, keadaan punya kenyataan. Pandemi yang tak kunjung hilang membuat semua aktivitas harus dilakukan secara virtual, sama seperti hubunganku dengannya.
“Kuliahnya udah selesai?” Notif WhatsApp darinya masuk.
“Belum, bentar lagi siap,” balasku singkat karena sedang menyimak penjelasan dari dosen.
“Oh, maaf,” balasnya lagi. Aku hanya melihat notifnya saja, tidak kubuka. ‘Kubalas nanti saja jika kuliahnya sudah selesai,” pikirku.
“Untuk pertemuan hari ini cukup, jangan lupa dengan tugas yang telah saya berikan. Wassalam,” ucap dosen mengakhiri perkuliahan pagi ini.
“Baik. Terima kasih, Pak.” Kata-kata andalan yang selalu dilontarkan oleh setiap mahasiswa secara bersamaan di akhir perkuliahan.
Kumatikan kembali laptopku dan mulai membaringkan diri di atas kasur karena lelah duduk terpaku di depan laptop dari pagi tadi. Kuraih ponsel yang tak jauh dari jangkauanku.
“Niel, aku udah selesai kuliahnya.” Aku membalas WhatsApp-nya yang tadi.
“ Oh. Iya, Zel,” balasnya singkat.
“Btw kenapa wa tadi, ada yang mau diomongin atau gimana?” tanyaku membuka topik.
“Eh, iya ni Zel, aku mau ngomong cuman aku bingung harus mulai dari mana,” ungkapnya ragu-ragu.
“Yaudah sih ngomong aja, kok tiba-tiba jadi aneh gini,” sahutku cetus.
“Sebenernya…eeemmm ngomongnya gimana ya, Zel. Kalo sendainya kita temenan aja gimana?” tanyanya yang seketika itu menghancurkan duniaku.
Aku diam tanpa jawaban, rasanya untuk berbicara sepotong kata pun aku sudah tak punya upaya, seperti tertimpa gedung 7 tingkat hancur berkeping-keping tanpa sisa. Segenap pertanyaan muncul di dalam hati, apa? Mengapa? Di mana salahnya? Secepat ini? Harus berakhir begini?
Air mata yang sedari tadi mendesak meminta untuk ditumpahkan, tapi kutahan, “Aku tidak lemah, kisah ini tidak boleh berakhir seperti ini,” ucapku dalam hati.
Setelah beberapa saat kuberanikan diri untuk bertanya. “Kenapa?” tanyaku dengan nada suara gemetar, hanya satu kata yang sanggup kulontarkan kala itu.
”Kamu tau kan kondisi kita sekarang gimana, kita jauh. Aku gak tau kamu di sana lagi apa, sama siapa, gitu juga sebaliknya. Aku gak mau nanti ada yang sakit hati antara kita.” Panjang lebar dia menjelaskan alasannya, aku hanya mematung mendengar penjelasannya.
“Jika memang begitu kenapa kamu harus hadir? Apa semua ini? Drama apa lagi ini?” Secara spontan pertanyaan demi pertanyaan keluar dari sayatan bibir kecil ini. Air mata semakin mendesak tak karuan meminta untuk keluar. ‘Apa akan mengubah keadaan jika aku menangis? Ah, bodoh sekali jika hal sepele seperti ini harus kutangisi,” batinku mencoba menguatkan diriku sendiri.
“Apakah kita bisa bicara sebentar saja via video call?” pintaku padanya dan dia mengiyakan.
Aku berusaha untuk tetap tenang, walau rasanya ingin sekali kusayatkan belati tajam tepat di hatinya, agar dia tahu sakit yang sedang kurasakan.
“Apakah ini satu-satunya jalan keluar dari hubungan ini? Jika masih memungkinkan untuk bertahan kenapa harus memilih perpisahan sebagai jalan. Kita sudah sama-sama dewasa, kita sudah sama-sama bisa berpikir, sampai kapan kita akan terus menjalani hubungan tanpa komitmen? Mengenal kembali orang baru dan memulai kembali dari awal bukanlah hal yang mudah, pertimbangkanlah ulang, hubungi aku saat kamu sudah yakin dengan keputusanmu,” ucapku sebelum menutup video call-nya.
Beberapa hari berlalu tanpa adanya komunikasi. Sakit, namun bagaimana caraku berlalu? Seperti candu yang semakin hari semakin membelenggu. Hati yang resah kian menggerutu, apakah akan berakhir sampai di sini? Pikiranku yang tak karuan terus menerawang menyusuri langit malam. Sesaat kemudian terdengar dering panggilan masuk dari ponsel yang sedari tadi kubiarkan tergeletak di atas meja riasku.
Sontak saja aku terkejut dan berdebar tak keruan, saat kulihat nama kontak “Daniel” yang terpampang di layar ponselku. Sebelum mengangkat panggilan videonya aku mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk segala keadaan yang akan terjadi malam ini. ‘Apapun yang akan terjadi setelah ini aku ikhlas Tuhan,’ ucapku dalam hati penuh keyakinan.
“Halo, Zel,” sapanya dari belahan bumi sana. ‘Oh Tuhan, aku sangat rindu dengan hangatnya sapaan ini,’ lirihku dalam hati.
“Halo, Zel… Zelline? Kamu bisa denger suara aku kan?” sapanya kembali yang memecahkan lamunanku.
“Eh… Oh… Iya, Niel, aku denger kok,” sahutku gelagapan, entah perasaan apa yang kini sedang berkecamuk tak keruan di sudut hati terdalam.
“Gimana kabarnya, kamu sehat-sehat kan?” tanyanya.
“Alhamdulillah, sehat. Kamu sendiri gimana? Sehat?” tanyaku balik.
“Alhamdulillah aku baik-baik aja,” jawabnya.
“Syukurlah. Oh iya, btw tumben-tumbenan telpon, kenapa emangnya?” tanyaku lagi.
“Jadi gak boleh ni telpon pacar sendiri?” Ketawanya cengengesan mencoba merayu jahil.
“Eh, masih dianggap ternyata. Kirain selama ini ngilang gara-gara udah punya doi baru,” jawabku sedikit jutek walau sebenarnya aku senang dengan bualannya tadi.
“Ya, nggak lah, just only you.” Jurus gombalan selanjutnya kembali dilontarkan.
“Mulai deh mulai… keluar jiwa pawang buayanya,” sindirku sambil memutar bola mata malas.
“Hahahaha,” tawanya pecah menggemakan seisi kamarku. “Tapi btw aku sebenernya video call kamu karna mau ngomongin sesuatu,” lanjutnya lagi.
“Ngomongin apa? Minta pisah?” tuduhku secara spontan.
“Yeee ni anak, belum juga kita ngomong udah suudzon duluan,” jawabnya kesal.
“Ya jadi?” tanyaku penuh kebingungan.
“Aku mau minta maaf atas sikap aku kemarin. Setelah aku pikir-pikir lagi, omongan kamu ada benernya juga. Ya emang sih kita sekarang cuman bisa tatap muka secara virtual, tapi selagi kita bisa saling ngejaga dan percaya, aku rasa kita bisa kok mempertahakan hubungan ini. Makasih, ya, karna selalu ada, dan maaf kalo aku pernah noreh luka,” jelasnya pajang lebar. ‘Aku tau kehilangan itu pasti, tapi doaku setiap hari, semoga bukan hari ini. Terima kasih, Tuhan,’ ucapku dalam hati penuh bahagia.
“Kamu serius?” Aku kembali bertanya.
“Ya iyalah, masa aku udah ngomong gitu, kamu malah nganggapnya becandaan, tega kamu ih, gak mau kawan lah,” jawabnya dengan rasa kesal yang buat-buat.
“Yaudah gapapa gak kawan, kita jadi temen aja,” timpaku sambil menahan tawa.
“Jeh kok temen sih, jadi kamu gak mau maafin aku ni ceritanya?” tanyanya putus asa.
“Temen hidup maksud aku, hehehe,” tawaku cengengesan yang sedari tadi kutahan.
“Hadeuh… dasar buaya betina,” jawabnya sambil memutar bola mata malasnya.
“Hahahaha!” kami saling tertawa bersama.
Hari yang kian kelabu seakan kini menunjukkan kembali pelanginya. Rasa yang dijalin dengan perantara kuota, semoga saja berakhir bahagia sampai tiba saatnya berjumpa. Terima kasih telah hadir semoga kamu menjadi titik berlabuh terakhir.
Penulis bernama Mella Agustia, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Ia juga merupakan anggota aktif di UKM Pers DETaK.
Editor: Sahida Purnama